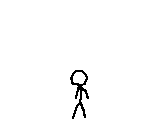“Apakah ia sedang bercanda? Tapi sepertinya ia tidak main-main,” gumam Riri dalam hati. Tidak pernah terbersit dalam pikiran Riri sebelumnya untuk berbuka puasa bersama di pesantren. Pesantren. Mendengar kata yang satu itu, seketika kenangan Riri menyeruak, kembali ke lembaran kehidupannya beberapa tahun yang lalu. Episode impian masa remajanya yang terlupakan.
“Aku ingin masuk pesantren, Ibu,” kata-kata Riri sangat mengejutkan ibunya, belum lama berselang sejak Riri memasuki gerbang cahaya Sang Maha Cinta. Ibu Riri menatap putrinya yang telah menginjak remaja itu dengan penuh tanda tanya. Ia sungguh tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Riri. Sebagai ibu yang baik, ia berusaha keras memahami dan menerima perubahan-perubahan dalam diri Riri walau sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab di dalam benaknya.
Riri memandang Ibu yang terdiam seribu basa. Ia tahu, Ibu sangat mencintai dan menyayanginya. Jarang sekali permintaannya ditolak dan rasa-rasanya kali inipun tidak jauh berbeda.
“Mengapa harus ke pesantren, Ri?” tanya Ibu sambil menghela nafas panjang. “Kamu tahu kan, kamu anak perempuan Ibu satu-satunya. Kalau kamu pergi, lantas siapa yang akan menemani Ibu? Apakah tidak bisa belajar agama Islam di sini saja?”
“Tapi aku ingin belajar di pesantren, Bu. Aku bisa belajar lebih mendalam dan konsentrasi di sana. Lagipula biayanya tidak mahal kok, Bu,” sanggah Riri.
“Bukan masalah biaya, Nak. Tapi Ibu tidak mau kehilanganmu,” mata ibunya mulai berkaca-kaca. Perlahan-lahan kristal-kristal bening mengaliri pipi tuanya. Sejak ia merestui Riri untuk berikrar syahadat, ia menyadari bahwa Riri bukanlah lagi putri kecil kesayangannya yang sama seperti yang dulu. Riri yang selalu duduk manis dan menuruti semua kata-kata dan perintahnya. Riri yang sering berceloteh riang dan bernyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan pulang dari rumah ibadah agama lamanya ke rumah. Betapa masa-masa itu telah lewat dan jarum jam dinding bergulir begitu cepat menancapkan kuku-kukunya di atas tumpukan kenangan.
“Kehilangan aku? Apa sih maksud Ibu? Aku gak ngerti. Lagipula Ibu sendiri yang bilang padaku kalau aku harus belajar dan beribadah dengan baik karena aku sendiri yang telah memilih jalan ini. Dan Ibu kan gak bisa mengajariku. Ibu bukan muslim,” Riri memandang ibunya dengan bingung.
Ibu Riri tidak dapat menahan lagi segala rasa yang menyesak di dada. “Pokoknya Riri tidak boleh masuk pesantren. Ibu sudah merestui Riri menjadi muslim dan Ibu memang mendukung Riri untuk belajar agama Islam dengan baik. Tapi bukan di pesantren. Riri tetap di sini. Tinggal sama Ibu,” itulah keputusan ibu Riri. Melepaskan semua harapan dan impian Riri untuk masuk pesantren. Malam menjadi abu-abu, melepaskan kerudung hitamnya untuk dipinjamkan pada hati Riri dan ibunya yang terbelah.
Roda kehidupan terus berjalan. Riri beranjak dewasa dan menyelesaikan pendidikannya di kota itu; ia tetap tinggal bersama Ibu. Ibu meninggal dunia ketika Riri baru saja menyelesaikan kuliahnya. Hari-hari yang berair, melarutkan semua kenangan Riri tentang Ibu. Hingga di akhir hidupnya, Ibu tetap tidak sejalan dengan Riri.
“Walau ibu Riri bukan muslim, tetapi Riri harus tetap mendoakannya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya,” begitu saran Bu Nur Nira setiap kali Riri menceritakan gundah hatinya.
“Kalau Riri mau berbuka puasa bersama di pesantren, nanti saya akan telepon Pak Kyai untuk memberitahukan maksud kedatangan kita. Apakah Riri juga mau menyediakan makanan untuk berbuka?” kata-kata Bu Nur Nira membawa Riri kembali dari lorong waktu yang sedetik lalu menyelimutinya.
“Di… Di pesantren, Bu? Pesantren mana?” tanya Riri gugup. “Aku belum pernah ke pesantren…” Jantung Riri seakan berhenti berdenyut. Impian masa remajanya berkibar-kibar kembali di hadapannya.
“Sebuah pesantren di pelosok Tangerang. Ibu baru satu kali ke sana. Santrinya ada sekitar tiga puluh orang yang mondok di sana. Semuanya ikhwan. Di sebelahnya ada pondok anak yatim. Masih satu kompleks dengan pesantren itu. Jadi Riri jangan kaget kalau tiba di sana. Suasananya ndeso banget,” kata Bu Nur Nira sambil tersenyum.
Riri menatap guru mengajinya. Pesantren. Akhirnya aku bisa menginjakkan kaki di pesantren.
“Oh begitu… Baiklah Bu. Kalau aku mau membawa makanan untuk berbuka, kira-kira aku beli di mana ya, Bu? Aku nggak tahu tempatnya. Untuk tiga puluh orang ya?” tanya Riri.
“Hmmm… Lebih baik sediakan makanan untuk empat puluh orang saja, Ri. Hari sabtu sore kita berbuka puasa dengan para santri, lalu esoknya kita berbuka puasa dengan anak-anak yatim. Riri sediakan makanan untuk para santri saja. Untuk acara berbuka dengan anak-anak yatim, sudah ada yang menyediakan makanan. Ibu-ibu majelis taklim di dekat sana sudah menyanggupi untuk menyediakan makanan,” jawab Bu Nur Nira.
Riri mulai menghitung-hitung dalam hati berapa jumlah uang yang harus disiapkannya untuk membeli makanan. “Harga nasi kotak sekitar tujuh ribu rupiah per kotak. Kalau empat puluh orang berarti dua ratus delapan puluh ribu rupiah. Tapi bagaimana kalau harga nasi kotaknya lebih dari itu? Coba kuhitung anggaran dana untuk ini: aku masih punya uang tiga ratus ribu rupiah sisa penghasilanku bulan lalu. Mudah-mudahan tiga ratus ribu cukup buat membeli makanan empat puluh orang,” benak Riri mulai berputar-putar memperhitungkan semuanya.
“Ri, nanti kita beli makanannya di Tangerang saja. Nggak usah bawa dari rumah, karena letak pesantren itu sekitar satu setengah jam dari Tangerang. Repot kalau harus bawa dari rumah. Kita kan naik bis umum,” kata Bu Nur Nira seraya beranjak dari kursi. “Ibu pulang dulu. Insya Allah hari Sabtu kita berangkat setelah shalat dzuhur, jadi kita bisa tiba di pesantren tepat waktunya berbuka.”
Riri mengangguk pelan. Pikirannya masih menghitung anggaran dana. “Wah, mesti beli makanan di Tangerang. Gimana kalau harganya lebih mahal?” bisik hati Riri gelisah.
Malam itu Riri tidur dengan pikiran berkecamuk. Di satu sisi mimpinya untuk ke pesantren tiba-tiba menjadi kenyataan, tapi di sisi lain ia khawatir mengecewakan Pak Kyai dan para santri di sana bila ternyata uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli makanan. “Ah aku yakin Allah pasti memberi jalan. Yang penting aku ingin silaturahim dengan saudara-saudaraku di sana. Entah bagaimana nantinya, aku jalani saja. Ibu, akhirnya keinginanku kesampaian juga,” itulah doa yang dibisikkan Riri sebelum rasa kantuk merenggutnya dari kesadaran.
******************
Sabtu siang, Riri sudah menunggu Bu Nur Nira dengan manis.
Sekali-sekali ia membetulkan kerudung biru muda yang dikenakannya. Tak
lama kemudian Bu Nur Nira datang dan mereka segera berangkat menuju
Tangerang. Riri sangat tegang. Setibanya di Tangerang, mereka mulai
mencari-cari kedai makanan. Sayup-sayup adzan berkumandang di kejauhan.
“Ashar di bumi Tangerang,” pikir Riri denganbersemangat. Setelah shalat Ashar, mereka masih mencari-cari kedai makanan untuk membeli makanan berbuka. Sudah setengah jam berputar-putar, tetapi mereka belum menemukan kedai makanan yang buka. Riri sudah separuh putus asa.
“Ayo… Jangan nyerah gitu dong, Ri. Insya Allah masih ada kedai makanan yang buka,” hibur Bu Nur Nira ketika ia melihat wajah Riri yang kebingungan.
Benar saja. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah kedai makanan sederhana. “Berapa harga satu bungkus nasi, Bu?” tanya Riri pada ibu pemilik kedai.
“Nasi pakai telur dan sayur atau nasi pakai ayam goreng dan sayur harganya enam ribu, Neng. Neng mau pesan berapa bungkus?” tanya ibu pemilik kedai ramah.
Riri menghitung dengan cepat. “Aku pesan empat puluh bungkus nasi, Ibu. Boleh pakai telur atau ayam,” katanya. “Alhamdulillah, ternyata lebih murah. Berarti masih ada sisa enam puluh ribu. Aku bisa beli kue.” Dengan riang, Riri membeli kue bolu dan buah-buahan seharga empat puluh delapan ribu rupiah. Total belanja Riri sore itu dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah. Riri membayar semua belanjaannya tanpa diketahui Bu Nur Nira.
Bu Nur Nira masih sibuk berbicara dengan pemilik kedai. Ternyata pemilik kedai bersedia mengantar mereka ke pesantren tersebut. “Ini sudah hampir maghrib, kalian harus tiba di sana tepat waktu, kalau tidak nanti mereka sudah berbuka puasa duluan. Biar saya yang antar saja. Nanti Bu Nur Nira memberitahu arah jalannya ya. Saya kurang paham daerah situ,” kata suami ibu pemilik kedai dengan ramah.
Beberapa menit setelah maghrib, mereka tiba di pesantren tersebut, Riri terbengong-bengong ketika memasuki kompleks pesantren itu. Bangunannya yang sederhana, hanya terbuat dari bilik-bilik kayu. Ada sebuah masjid kecil di depan kompleks dan sebuah rumah batu bata yang didiami oleh Pak Kyai beserta keluarganya.
“Ini toh yang namanya pesantren. Akhirnya aku bisa menjejakkan kaki di sini. Suasana yang tenang, pas banget untuk berdzikir dan shalat malam. Oh Ibu, seandainya Ibu berada di sini sekarang,” dengan penuh haru yang memenuhi dadanya Riri melangkah memasuki pesantren itu. Di dalam rumah Pak Kyai sudah berkumpul seluruh santri, siap untuk bersantap bersama. Riri larut dalam suasana kekeluargaan. Seluruh penghuni pondok pesantren beserta keluarga Pak Kyai berbuka puasa bersama dengan makanan sederhana yang dibawa Riri. Bu Nur Nira dapat melihat wajah Riri yang bercahaya, penuh kegembiraan malam itu.
“Mbak Riri baru pertama kali ya ke pesantren?” tanya Pak Kyai ramah.
“Iya, Pak,” jawab Riri dengan sumringah. “Di sini enak ya suasananya. Tenang, adem, sunyi, sepi, rasanya aku gak mau pulang ke Jakarta deh, Pak. Aku ingin tinggal di sini.” Riri menghirup nafas dalam-dalam sehingga udara segar memenuhi rongga dadanya yang bahagia. Tapi rasanya gak bisa. Ya sudah aku nikmati saja saat-saat menyenangkan di pesantren ini sekarang. Bulanpun tersenyum pada Riri malam itu.
Keesokan harinya, Riri dan Bu Nur Nira sibuk membantu ibu-ibu majelis taklim menyiapkan acara berbuka puasa bersama anak-anak yatim. “Mbak Riri, nanti Mbak bicara sedikit ya di depan jamaah. Cerita tentang asal mulanya Mbak Riri tertarik pada agama Islam dan kemudian memeluknya,” ujar seorang ibu.
“Cerita? Boleh aja. Aku senang sekali berbincang-bincang dengan teman-teman,” jawab Riri dengan semangat.
Acara berbuka puasa bersamapun berjalan lancar. Dunia Riri turut merekah seiring dengan senyum kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Dengan bersemangat Riri menceritakan asal mulanya ia tertarik memeluk agama Islam. Hati-hati mereka yang hadir, termasuk Pak Kyai dan para santri yang turut ambil bagian acara tersebut, bagai diselubungi cahaya putih kedamaian. Di bawah tatapan Sang Maha Cinta, Riri berbicara dengan semangat.
Jam telah menunjukkan pukul setengah delapan malam ketika acara itu usai. Shalat tarawih akan segera dimulai. Dengan berat hati, Riri dan Bu Nur Nira harus segera pulang ke Jakarta. Bis terakhir cuma ada sampai jam delapan. Sebelum pulang, seorang ibu dari majelis taklim menghampir Riri.
“Mbak Riri, ini ada sedikit sumbangan dari ibu-ibu di sini. Jumlahnya mungkin tidak banyak. Tetapi insya Allah kami semua ikhlas. Ini untuk Mbak Riri, semoga Mbak Riri tetap istiqomah di jalan-Nya. Kami semua terharu mendengar cerita Mbak Riri tadi,” ibu itu menyelipkan setangkup amplop putih ke dalam tangan Riri.
Riri terkejut sekali. “Apa ini, Bu? Saya… Saya…” Riri tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat.
“Ambillah, Mbak. Sebagai tanda cinta dari kami dan teriring doa kami semoga Mbak istiqomah,” jawab ibu itu sembari memeluk Riri.
Riri pulang ke Jakarta dengan termenung-menung. Hujan deras membasahi bumi Tangerang. Bu Nur Nira juga tidak banyak bicara selama perjalanan pulang.
“Bu, tadi aku dikasih amplop ini sama ibu-ibu majelis taklim,” kata Riri pelan. Bu Nur Nira tersenyum hangat. “Alhamdulillah. Ambillah Ri. Syukuri semua nikmat yang Allah berikan.”
Riri membuka amplop putih itu. Ada lembaran-lembaran uang lima puluh ribuan, sepuluh ribuan dan seribuan. Dengan hati-hati Riri menghitungnya. Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah. Jantung Riri seakan berhenti berdetak. Jumlahnya tepat dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah. Langitpun luruh bersama cahaya cinta dari pesantren impian.
****** Selesai ******